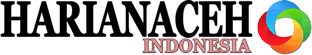Penulis: Hastuty Regar
WACANA pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi di Indonesia memunculkan beragam reaksi. Rencana ini tertuang dalam revisi UU Mineral dan Batubara (Minerba) yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif dari DPR RI di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyatakan usulan pemberian izin usaha tambang secara lelang atau prioritas pada perguruan tinggi sejatinya muncul dari pemerintah dengan alasan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Beragam reaksi baik itu pro maupun kontra memicu ditengah rancangan UU Minerba ini. Pemberian pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi diusulkan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) usulan tersebut sejak tahun 2016. Ketua Umum APTISI, Budi Djatmiko, menyebut bahwa usul agar universitas diberikan hak untuk mengelola tambang datang dari lembaganya.
Forum Rektor Indonesia mendukung wacana tersebut agar perguruan tinggi dapat mengelola tambang yang diusulkan masuk dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia Didin Muhafidin menilai langkah ini sangat positif, asalkan perguruan itu telah memiliki status badan hukum (BHP) dan unit usaha sendiri.
Menurut Didin, pelibatan perguruan tinggi dalam mengelola tambang akan meningkatkan pendapatan lembaga, terutama bagi perguruan tinggi swasta besar yang memiliki yayasan dengan unit usaha. Pendapatan tambahan ini diharapkan dapat mengurangi beban mahasiswa, misalnya dengan menekan kenaikan SPP atau biaya operasional lainnya.
Sementara itu, pihak yang kontra adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Mereka menolak keras wacana ini karena khawatir pemberian izin usaha tambang pada kampus akan memberangus pemikiran kritis perguruan tinggi. Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga menolak wacana ini. Koordinator Pusat BEM SI Herianto mengatakan fokus perguruan tinggi adalah mendidik dan mengajar, bukan terlibat dalam aktivitas bisnis seperti pengelolaan tambang.
Sependapat dengan hal tersebut Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid menolak dengan tegas wacana ini. Kekhawatiran utamanya adalah potensi pergeseran fokus perguruan tinggi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) ke ranah bisnis pertambangan. Ia melihat dampak yang akan ditimbulkan jika kampus terlibat dalam pengelolaan tambang, yaitu integritas akademik dipertaruhkan, suara kritis kampus makin parau ketika terjadi ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang, dan terlenanya kampus pada bisnis hingga melalaikannya dari visi misinya sebagai lembaga pendidikan.
Pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi memungkinkan adanya otonomi yang membuat perguruan tinggi mencari pendapatan mandiri. Usulan ini sejatinya akan membelokkan orientasi perguruan tinggi. Disorientasi pendidikan ini terjadi sebagai konsekuensi industrialisasi pendidikan (PT PTN BH).
Pada 2000, sejumlah PTN di Indonesia berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Lalu pada 2009 bentuk BHMN berganti nama menjadi badan hukum pendidikan (BHP) pemerintah sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. UU tersebut kemudian dibatalkan oleh MK pada 31 Maret 2010 yang membuat pemerintah mengeluarkan PP No. 66 Tahun 2010 yang mengembalikan status perguruan tinggi BHMN menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Status tersebut tidak bertahan lama setelah terbitnya UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Saat itu seluruh perguruan tinggi eks BHMN, termasuk yang telah berubah menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah, ditetapkan sebagai PTN BH.
Lahirnya status kampus sebagai PTN BH inilah yang membuat kampus makin kental dengan kapitalisasi pendidikan. Akibatnya, orientasi kampus tidak lagi menawarkan pendidikan dengan biaya murah kepada calon mahasiswanya. Yang terjadi, biaya kuliah makin tinggi, apalagi setelah ada ketentuan UKT mahasiswa.
Status kampus sebagai PTN BH juga memiliki sejumlah konsekuensi. Salah satunya ialah kebebasan dalam mencari sumber pendapatan menjadikan kampus lebih fokus pada aktivitas komersial dan mengabaikan misi pendidikan publik. Program-program yang lebih “menguntungkan” secara finansial menjadi prioritas. Sedangkan program-program yang lebih berfokus pada pengabdian masyarakat atau ilmu dasar terpinggirkan. Kampus pun berada di persimpangan jalan, memilih kepentingan finansial atau mengutamakan tanggung jawab sosial sebagai institusi pendidikan.
Hal ini juga menunjukkan terjadinya disfungsi negara yang seharusnya berperan sebagai raa’in dan junnah yang bertanggung jawab atas pemenuhan publik atas kebutuhan akses ke Perguruan Tinggi dan pengelolaan tambang sebagai harta milik umum. Bukan menyerahkan pengelolaan tambang kepada ormas atau kampus.
Pengelolaan tambang sebagai harta milik umum tidak seharusnya diserahkan pada pihak lain. Ini merupakan tanggung jawab negara dalam mengelola dan mengembalikan hasilnya kepada masyarakat. Kebijakan ini terjadi karena penerapan sistem sekuler kapitalisme yang memberikan kebebasan bagi siapapun untuk menguasai harta milik rakyat.
Sistem sekuler kapitalisme melahirkan kebijakan kapitalistik yang mengubah orientasi pendidikan untuk mengejar materi. Dalam sistem kapitalisme, pembiayaan ditanggung orangtua atau personal sehingga menjadi sangat berat dan menutup peluang mahasiswa yang miskin mengenyam pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi sangat mahal yang hanya bisa mengenyamnya adalah orang-orang yang bermodal.
Orientasi pendidikan dalam Islam tidak sama dengan sistem sekuler kapitalisme yang berorientasi pada materi semata. Bukan juga merupakan akomoditas yang bisa diukur melalui untung dan rugi. Pendidikan dalam Islam menjadi sektor yang sangat krusial yang dijamin pemenuhannya oleh negara secara gratis. Negara memastikan seluruh warganya mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Mengoptimalkan pelayanan agar selalu mendapatkan kesempatan yang sama dalam menggali potensi setiap warga.
Oleh sebab itu perguruan tinggi dapat dijangkau oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Karena perguruan tinggi tersebut berfokus membentuk syaksiyah Islamiyah (kepribadian Islam) dan generasi unggulan yang memberikan karya terbaik untuk kontribusi kemaslahatan umat. Pendidikan juga berperan mempersiapkan generasi menjadi para ulama dan ahli di berbagai aspek kehidupan.
Islam menetapkan layanan pendidikan harus diberikan secara gratis. Pembiayaan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi ditanggung negara melalui baitul mal. Fasilitas pendidikan yang prima tersedia di seluruh pelosok negeri serta ditunjang dengan anggaran pendidikan yang sangat besar. Kas negara (baitul mal) yang memiliki sumber pemasukan yang melimpah akan sangat mampu menjadi faktor pendukung dalam menyediakan seluruh kebutuhan belajar dan mengajar. Salah satu pemasukannya adalah dari hasil pengelolaan tambang. Negara wajib mengelolanya untuk dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk sarana umum termasuk layanan pendidikan.
Maka Islam mengharamkan pengelolaan pertambangan oleh individu atau swasta sebagaimana yang terjadi hari ini. Tambang adalah milik umum, wajib dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk berbagai pelayanan negara untuk kemaslahatan rakyat.
Adapun dalil yang dijadikan dasar untuk pengelolaan barang tambang yang berjumlah banyak dan tidak terbatas sebagai bagian dari pemilikan umum adalah hadis yang diriwayatkan dari Abidh bin Hamal al-Mazaniy,
“Sesungguhnya dia bermaksud meminta (tambang) garam kepada Rasulullah maka beliau memberikannya. Tatkala beliau memberikannya, berkata salah seorang laki-laki yang ada di dalam majelis, ‘Apakah Anda mengetahui apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang telah Anda berikan itu laksana (memberikan) air yang mengalir’. Akhirnya beliau bersabda, ‘(Kalau begitu) tarik kembali darinya.’” (HR Tirmidzi).